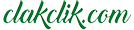Perundungan atau bullying di lembaga pendidikan dapat menjadi ukuran terjadinya tindakan-tindakan lain yang membahayakan. Minimnya kemampuan berempati ditengarai menjadi salah satu faktor langgengnya perilaku bullying di sekolahan. Pendidikan karakter dari para guru dan keluarga diharapkan dapat membantu memutus mata rantai kebencian akibat perundungan.
Editorial | Clakclik.com | 24 Februari 2024
selama ini sudah banyak kisah bullying yang terungkap, namun banyak juga kisah yang belum dan tidak terungkap. kisah-kisah yang terungkap laksana fenomena gunung es. kisah yang tidak terungkap berpeluang lebih besar daripada yang terungkap.
Kejadian tersebut kian menambah daftar panjang keprihatinan akibat dampak buruk yang
yang harus dipahami oleh semua pihak bahwa dampak bullying tidak bisa dianggap sepele. Korban bullying bisa mengalami trauma yang dapat membentuk rasa benci mendalam terhadap para pelaku. Ibarat api dalam sekam, kebencian yang terus menumpuk dapat berubah menjadi tindakan yang dapat membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain.
Ironisnya, persoalan perundungan seakan begitu sulit dicabut dari lingkungan pendidikan. Bahkan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menyatakan perundungan adalah satu dari tiga dosa besar pendidikan. Dua lainnya adalah kekerasan seksual dan intoleransi. Namun, sekalipun telah ”ditetapkan” menjadi dosa besar, perilaku perundungan di lingkungan sekolah masih belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada kurun 2019-2 Agustus 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di sekolah hanya mengalami penurunan saat pandemi. Pada 2019, jumlah kasus kekerasan di sekolah mencapai 8,6 persen dari total kasus kekerasan pada anak. Jumlah ini menurun hampir separuh selama masa pandemi, yakni menjadi 4,9 persen pada 2020 dan 4,2 persen pada 2021.
Namun, ketika kondisi pandemi mulai mereda dan pembelajaran kembali berlangsung di sekolah, kasus kekerasan pada anak di dunia pendidikan kembali meningkat. Pada 2022, persentase kasus naik menjadi 7,6 persen atau bertambah 3,4 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun ini, sejak Januari hingga awal Agustus, angka kekerasan pada anak di sekolah terus naik hingga 8,7 persen atau hampir sama seperti kondisi sebelum pandemi.
Ironisnya lagi, sosok guru yang seharusnya melindungi anak-anak ternyata turut menjadi pelaku dari tindak kekerasan itu. Dari data selama kurun waktu yang sama, rata-rata pelaku kekerasan yang merupakan guru mencapai 4,4 persen dari total jumlah pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah belum menjadi tempat yang sepenuhnya aman bagi anak-anak dari tindak kekerasan, termasuk perundungan.
Jika diteliti lebih dalam, anak laki-laki cenderung lebih rentan mengalami tindak kekerasan di sekolah dibandingkan anak perempuan. Rata-rata jumlah kasus kekerasan pada anak laki-laki di sekolah selama 2019 hingga Juli 2023 mencapai 12,4 persen. Jumlah ini lebih banyak 2,5 kali lipat dibandingkan anak perempuan yang proporsi kasusnya sebanyak 4,7 persen.
Terkait dengan bullying yang dilakukan oleh guru, sosok pendidik ini lebih kerap menyasarnya pada anak laki-laki, dengan rata-rata kasus sebesar 5,80 persen. Untuk kasus kekerasan yang dilakukan guru dan mengarah pada anak perempuan berkisar 3,78 persen. Adapun anak laki-laki lebih rentan menerima kekerasan secara fisik, yakni rata-rata 38 persen dari total jenis kekerasan yang dialami korban. Sementara, anak perempuan mayoritas mengalami kekerasan seksual dengan rata-rata 56,2 persen.
Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi tindakan bullying tersebut. Namun, salah satu penyebab yang tak dapat disangkal adalah ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Perilaku bullying hanya akan terjadi bila pelaku memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada korban. Kuasa ini dapat berwujud kekuatan fisik, umur, kondisi ekonomi, status keluarga, kecerdasan intelektual, dan lain sebagainya.
Di samping ketimpangan relasi kuasa, faktor lain yang dapat melatarbelakangi bullying adalah kondisi lingkungan sekitar yang permisif terhadap perilaku perundungan. Hal ini dapat dilihat dari data Programme for Internasional Student Assessment (PISA) tahun 2018. PISA merupakan program dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD) untuk mengukur kualitas pendidikan di berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia.
Berdasarkan data PISA 2018, sebanyak 57,1 persen pelajar Indonesia menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa ikut dalam tindakan bullying adalah hal yang salah. Jumlah ini merupakan yang terkecil dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya seperti Filipina (lebih dari 78,5 persen), dan Singapura (mencapai 95,7 persen).
Persoalan perundungan di Indonesia cukup pelik karena hasil riset menunjukkan 27 persen responden Indonesia menyatakan tidak suka ketika melihat orang lain membela korban perundungan. Jumlah ini kembali menjadi yang terbanyak dibandingkan beberapa negara lainnya. Ironisnya lagi, setidaknya ada 25,6 persen responden di Indonesia merasa tidak terganggu ketika tak ada satu orang pun membantu dan membela korban bullying. Sekali lagi, jumlah ini relatif lebih besar dibandingkan negara lainnya. Hal ini memberikan petunjuk bahwa lingkungan sosial di Indonesia, termasuk di sekolah-sekolah, cenderung permisif terhadap perilaku bullying.
Kondisi lingkungan sosial yang permisif seperti itu bisa disebabkan oleh minimnya empati di dalam diri masyarakat ataupun pelajar akibat kultur kekerasan yang sudah menjadi sebuah ”kewajaran” . Di tengah situasi demikian, melatih kembali kemampuan berempati dapat menjadi perisai terbaik untuk mencegah timbulnya perilaku bullying.
Empati adalah soal melatih dan merawat akal serta budi supaya peka terhadap orang di sekitar. Peran melatih dan merawat ini diharapkan diemban oleh orang-orang terdekat anak, yakni orangtua dan guru. Tak hanya cukup melalui nasihat semata, pelatihan empati juga harus melalui aksi nyata. Ini supaya anak tidak hanya sekadar mengetahui perasaan orang lain (empati kognitif), tetapi juga ikut merasakan perasaan orang lain tersebut (empati afektif). Dengan demikian, dengan hati yang mampu merasa, diharapkan anak memilih untuk menjauhi perilaku perundungan dan mengawali langkah memutus mata rantai kekerasan di sekolah.